(Apresiasi atas Gagasan Bapak Yosni Herin)
Oleh Steph Tupeng Witin
Wartawan, sedang merampungkan buku kumpulan Cerpen 'Bukit yang Congkak'
"Kesaksian harus diberikanAgar kehidupan terus terjaga" (Rendra, "Potret Pembangunan dalam Puisi")PENULIS tertarik dengan tulisan Bapak Yosni Herin - salah satu dari sekian 'birokrat' selain Bapak Herman Musakabe yang terus menulis perihal sastra NTT yang masih 'terpencil' meski eksis, dari jagat sastra nasional (Pos Kupang, 5/1). Meski 'terpencil' para sastrawan muda yang lahir dari rahim NTT terus setia berkarya meski karya-karya itu hanya 'mampu' mengisi lembaran-lembaran media massa lokal dan majalah ilmiah kampus maupun buletin-buletin komunitas yang terbatas ruang pendistribusiannya.Perdebatan seputar predikat sebuah karya sastra, entah berlevel lokal atau nasional maupun kriteria yang menempatkan sebuah karya itu bermutu atau tidak menurut ukuran tertentu, mengungkapkan kegelisahan perihal eksistensi sebuah karya sastra. Di balik perdebatan itu yang biasanya 'dimenangkan' oleh 'golongan kuat' (sastrawan nasional), kita masih menemukan bahwa di antara deretan pegunungan, perbukitan bebatuan dan sedikit tanah di NTT ini, muncul karya-karya sastra yang terus diasah dan dikembangkan melalui ruang-ruang sastra yang bisa menampung. Perdebatan mesti dibaca dalam kerangka untuk semakin mengasah kemampuan berkarya sastra khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa di 'nusa lontar' ini. Meski karya-karya sastra kita di NTT belum mampu menembus 'pasaran' sastra nasional, aktivitas sastra mesti terus digelorakan oleh siapa dan komunitas mana pun dan ombak bakat serta kemampuan harus terus digelombangkan agar ada kemampuan yang semakin terasah dan ada bakat yang menemukan ruang pengungkapannya. Meski sastra kita masih 'terpencil' nilai yang terkandung dalam setiap karya sastra mesti mendapatkan akses perhatian yang intens. Betapapun 'terpencil' sebuah karya sastra maupun tulisan yang terekam di halaman media lokal, ia menghadirkan beragam kandungan nilai yang mesti sedikitnya 'berpengaruh' dalam ranah kehidupan sosial politik kita. Setiap karya sastra betapa pun sederhana dan kecilnya mengandung kritik sosial sebagai bagian dari partisipasi sastrawan/penulis untuk membangun kehidupan bersama secara manusiawi. Tulisan ini berikhtiar menghadirkan nilai kritik sosial dalam karya sastra sebagai 'kado' bagi para birokrat dan politisi kita untuk mengabdi kepada kemanusiaan rakyat kecil yang 'berjasa' mengeksiskan mereka di 'kursi'. Kritik Sosial : Cermin Wajah KitaKritik sosial merupakan penilaian atau pengujian terhadap realitas masyarakat pada sebuah rentang waktu tertentu. Dalam ranah politik, kritik sosial sering dimaknai sebagai sebuah upaya mencari kelemahan-kelemahan lawan politik agar dijadikan senjata penjegal dalam kompetisi politik. Makna implisit inilah yang seringkali menjadi titik yang mengaburkan makna kritik sosial. Umumnya, kritik sosial mendambakan perubahan ke arah perbaikan. Kritik sosial berorientasi ke masa depan. Prediksi senantiasa mengandaikan pengetahuan dan kemampuan merangkai beragam relasi sosial menjadi kenyataan. Para sosiolog mendefinisikan masa depan sebagai sebuah kekenyataan (the future is real). Kenyataan itu tidak terkungkung dalam sekat masa lampau atau masa kini, tetapi menjangkau kemungkinan dan alternatif-alternatif agar dirangkai menjadi sebuah bangunan kenyataan masa depan yang dilandasi oleh pengalaman kemarin dan kenyataan hari ini. Kritik sosial diibaratkan sebagai sebuah cermin. Melalui medium cermin kritik sosial ini kita dapat melihat pantulan wajah kita yang sesungguhnya. Bila kita memandang cermin, kita cenderung melihat kejanggalan dan kekurangan yang terpantul. Maka kritik sosial pun kerap menghadirkan kelemahan dan kekurangan yang sebetulnya memiliki imperatif profetis yang mengingatkan, menyadarkan dan membangunkan kesadaran kita untuk selalu berbenah diri dan 'terjaga'. Di titik ini kita perlukan keterbukaan untuk menerima kritik sosial dengan dada yang lapang. Kritik sosial ibarat gumpalan tanah merah yang ditambalkan tukang periuk pada dinding kemanusiaan kita yang mudah retak karena rapuh. Para pengeritik sosial pun dituntut untuk menghadirkan kritik sosialnya secara obyektif, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data-data yang akurat dan benar dengan cara-cara penyampaian yang beretika. Dengan demikian kritik sosial dapat diterima dan memiliki pengaruh dalam mengubah pola perilaku yang menyimpang dari ethos dan moralitas. Sastra dan Kritik SosialPada tahun 1974, Rendra mengubah sebuah puisi berjudul Kesaksian yang dua bait terakhirnya saya kutip pada awal tulisan ini. Puisi ini merupakan kesaksiannya atas situasi sosial politik dalam masa Orde Baru. Saat itu republik ini tengah tenggelam-terhanyut dalam gemuruh badai pembangunan. Di tengah peradaban pembangunan, semua membisu. Atas nama pembangunan, jangan tanya siapa itu manusia, apa itu konsep masyarakat adil dan makmur - santapan pidato pejabat dan persoalan pemerataan pembangunan. Cukup tahu bahwa pertumbuhan ekonomi bangsa dalam keadaan stabil. Selama masa itu bahkan hingga saat ini, terdengar budaya kor anggota DPR/DPRD, perbedaan pendapat yang identik dengan pembangkangan dan karena itu mesti disingkirkan, para mahasiswa berteriak lantang tentang aparatur yang bersih dan berwibawa tetapi tetap saja ada penayangan koruptor, rakyat berteriak tentang keadilan di depan hukum tetapi pengadilan kita hanya sebuah komedi murahan yang mudah ditebak hasil akhirnya. Karya sastra yang mengangkat permasalahan sosial - politik merupakan bukti kebersatuan sastrawan/penulis dengan realitas. Sastrawan bersatu dengan kenyataan harian. Ia terlibat secara intens dalam pergulatan sosial-politik-kemanusiaan bangsa. Sastra menjadi medium untuk mengungkapkan ketajaman naluri dan kepekaan rasanya sebagai bentuk tanggapan atas realitas sosial-politik itu. Maka ketika kita membaca karya sastra, sesungguhnya kita sedang memandang kembali panorama realitas sosial-politik harian kita dengan lebih intens dalam 'wajahnya' yang 'baru'. Kita dengan lebih mendalam 'memandang' dan membaca realitas kemiskinan, keterbelakangan, rendahnya mutu pendidikan, penyalahgunaan kedudukan dan kuasa sebagainya.
'Realitas baru' ini pun menjadi syarat keprihatinan penulis/sastrawan sebagai makhluk sosial yang menghadirkan kritik sosial untuk menjadi titik perhatian dalam pengambilan kebijakan publik. Sastrawan/penulis 'menjeritkan' keluhan, tangisan dan teriakan nurani kaum kecil yang sering menjadi obyek obralan politisi selama berlangsungnya musim-musim kampanye. Menurut Sapardi Djoko Damono, karya sastra menghadirkan simpati sastrawan terhadap hidup kaum kecil. Kaum pinggir adalah lambang kepincangan sosial sekaligus ironi di tengah gemerlap hidup segelintir kaum berpunya dan berkuasa. Selain pengemis, potret kaum terpinggir mewajah dalam kehidupan tukang becak, pegawai rendahan yang digaji seadanya, perempuan kampung yang miskin, pelacur yang mengharapkan hidup dari kaum lelaki, guru kecil-terpencil yang tidak berkecukupan dan sebagainya. Tetapi justru orang-orang kecil inilah yang menampilkan kehendak yang kuat, harapan yang kokoh, teladan hidup mengagumkan dan kesabaran yang tinggi. Mochtar Lubis dalam cerpen Hidup Singkat si Comat yang Bahagia menampilkan Comat, pegawai rendahan pada sebuah instansi yang gajinya tidak cukup dan harus mengayuh becak di malam hari. Saat mengayuh becaknya, Comat terlempar dari becaknya tersambar mobil pejabat yan melaju dengan kecepatan yang tinggi. Comat akhirnya mati karena darah yang dibutuhkan untuk operasinya diberikan kepada seorang pembesar negara yang malam itu juga menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Hidup pembesar negara lebih utama dari hidup Comat. Pramoedya Ananta Toer dalam novel Korupsi menghadirkan dilema klasik manusia: jujur atau korupsi? Pegawai yang jujur berarti membiarkan keluarga hidup sengsara. Lalu? Akhirnya ia memutuskan untuk mengambil langkah korupsi. Tekanan kebutuhan hidup keluarga akan uang akhirnya meruntuhkan moralitas keluarga. Rendra dalam sajak Bersatulah Pelacur-Pelacur Jakarta melukiskan ikhtiar para pelacur untuk menaikkan tarif dua kali lipat, membuat pemogokan dan berdemonstrasi hingga seluruh masyarakat setuju untuk memulihkan martabat mereka sebagai manusia buangan. Suara yang Tetap 'Terpencil'Pertanyaan yang relevan untuk direfleksikan adalah: seberapa jauh efektivitas pengaruh karya sastra bagi perubahan kehidupan? Banyak karya sastra yang mengritik ketimpangan pembangunan tetapi ketimpangan itu kian menjadi-jadi. Karya sastra banyak yang mengangkat tema korupsi dalam struktur birokrasi eksekutif-legislatif-yudikatif-kepolisian, tetapi semakin hari korupsi semakin gila di negeri ini. Jadi apa yang dapat ditarik perihal kritik sosial dalam karya sastra Indonesia? Sampai hari ini, kritik sosial dalam karya sastra Indonesia adalah sebuah suara yang tetap 'terpencil' di tengah jagat kehidupan bangsa. Dalam bahasa Sapardi Djoko Damono, kritik sosial dalam sastra Indonesia laksana lebah tanpa sengat. Kritik sosial dalam karya sastra Indonesia tidak mampu 'menyakiti', apalagi berdaya 'memaksa' manusia untuk mengubah pola perilaku dan pola hidup. Sastra hanya sampai pada tahap yang membuat orang merasa risih, geli atau jengkel. Kalaupun ada yang hendak menindasnya, orang dapat melakukan tanpa risiko apa pun. Meski demikian, sastrawan masa kini mesti terus berkarya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persoalan kemasyarakatan. Ia dapat menjadi pengamat aktif yang menyaksikan, mencatat dan kemudian merefleksikan dan menuangkannya dalam bejana karya sastra entah berupa puisi, cerpen, novel maupun roman. Di sini sastrawan/penulis menjalin relasi dengan sejarah karena tema dan topik yang diangkat eksis dalam lintasan sejarah yang beruas waktu. Penyair/sastrawan menjadi pencatat sejarah. Kesungguhan dalam berkarya akan menghasilkan karya sastra yang bermutu dan bernilai bagi kehidupan. Perjalanan hidup dan karya sastrawan mesti berakhir pada titik penemuan nilai dan makna di tengah gebyar panorama yang sensasional. Hanya dengan jalan ini karya sastra tetap menunjukkan jati diri kehadirannya dan bisa menjadi medium untuk menakar sikap dan keterlibatan kita terhadap persoalan masyarakat. Kritik sosial dalam karya sastra, betapa pun kecil dan sederhana, biarpun hanya bisa memenuhi halaman media massa lokal dan buletin komunitas terbatas, pada titik tertentu dapat membantu pengambil kebijakan untuk melangkahkan 'kaki' kebijakannya politik-publiknya secara tepat dan melaksanakan pembangunan yang memenuhi rasa keadilan rakyat. Sastra berperan mendidik, terutama mengembangkan daya berpikir kritis dan mempertajam kepekaan perasaan manusia. Penulis hendak menutup tulisan ini dengan mengutip baik sajak sastrawan Rusia, Boris Pasternak berikut ini: Dan aku tegak berdiriDi sekitar hingar bingar kaum farisiHidup tak semudah menyeberangi air kali Sajak ini menggambarkan kebimbangan Hamlet sebagai kebimbangan Nabi Isa dalam menerima beban salib kematianNya yang tragis. Bait sajak ini mengingatkan kita: betapa kehidupan kita hari-hari ini maupun di waktu yang akan datang tidak akan pernah sepi dari warna kebisingan tuduh menuduh, saling mempersalahkan yang tumbuh bersamaan dengan keruwetan dan kemajemukan dimensi kehidupan. Kita harus menunjukkan simpati yang mendalam terhadap orang-orang yang mengalami semua ini. Kepercayaan kita sebagai manusia akan tetap diuji: apakah kita sanggup mempertahankan kemerdekaan jiwa meski dengan payung ketakutan agar kemudian dapat membantu sesama yang tengah dirundung keruwetan dan beban kehidupan yang berat ini? Bagaimana peran kemanusiaan penuh risiko ini dapat kita wujudkan di tengah bangsa yang kian tidak jelas ini? Sastra dan kesenian pada umumnya merupakan komponen peradaban manusia. Ia memiliki relevansi untuk bekerja sama dengan disiplin-disiplin kehidupan lain dalam membangun kultur bangsa yang berkualitas. Sastra berperan memelihara kelembutan hati, kepekaan perasaan, ketajaman intuisi, kedalaman jiwa, kearifan sikap sosial dan keluasan wawasan hidup. Bahkan sastra merupakan sebuah jalan memasuki dunia spiritual. Naguib Mahfouz, sastrawan peraih nobel 1998 asal Mesir menulis bahwa sastra selalu bekerja sama dengan agama dalam menyebarkan nilai-nilai luhur dan memperbaiki taraf kehidupan umat manusia. Bagi rekan-rekan sastrawan muda NTT, marilah terus berkarya dalam diam, sunyi. Karya-karya kita meski 'terpencil' dalam takaran sastra nasional, tetap memainkan peran kritik sosial dalam skala sederhana bagi siapa pun yang tersentuh nuraninya. Karya-karya kita bisa membantu membentuk opini, gagasan dan merangsang kemampuan berpikir orang lain. Teruslah berkarya dan biarkan sejarah sastra lokal NTT mencatat namamu! *



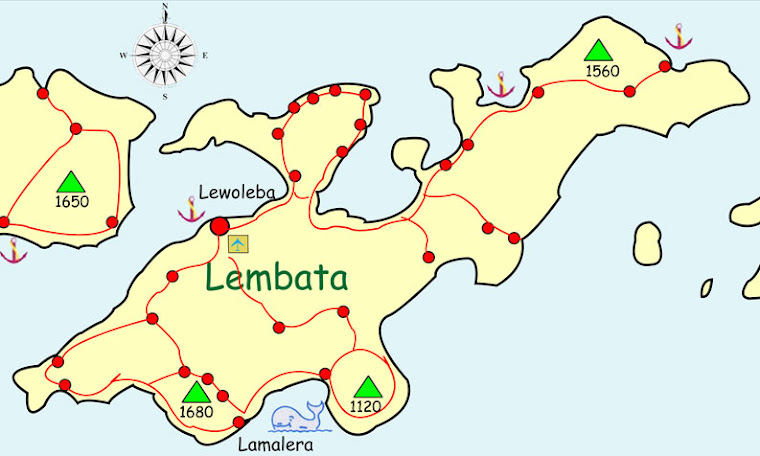
Tidak ada komentar:
Posting Komentar